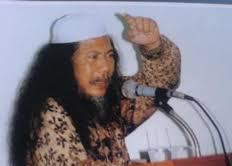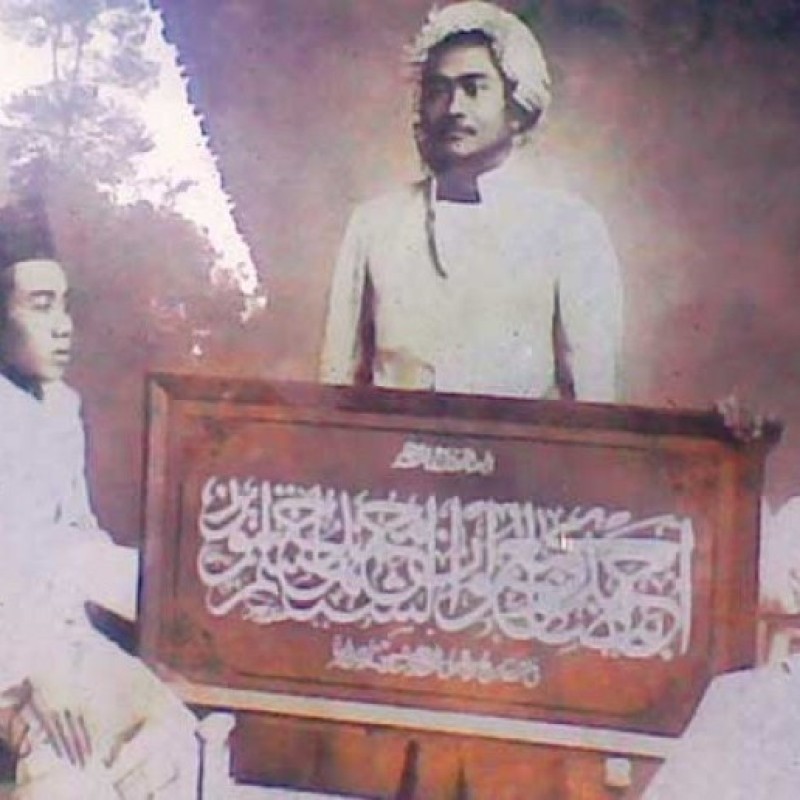KH Mukhdzir bin Zainal Arifin: Ulama Penulis dari Cilacap
NU Online · Senin, 5 Mei 2025 | 11:05 WIB
Roikhatul Jannah
Kolomnis
KH Mukhdzir bin Zainal Arifin merupakan seorang ulama, tokoh masyarakat, dan aktivis Nahdlatul Ulama (NU) dari Cipari yang dikenal luas di wilayah Cilacap dan sekitarnya. Dengan pandangan hidup yang tegas dan komitmen terhadap nilai-nilai keislaman, beliau menjadi sosok panutan serta rujukan masyarakat dalam berbagai persoalan, khususnya yang berkaitan dengan fikih, tauhid, dan tasawuf. Kemampuannya dalam menjawab berbagai persoalan keagamaan menjadikan beliau sebagai “kiai kampung” yang berperan aktif dalam forum bahtsul masail, baik di tingkat NU Cilacap maupun wilayah Jawa Tengah.
KH Mukhdzir lahir pada tanggal 1 Agustus 1930 di Dusun Sidadadi, Desa Mulyadadi, Kecamatan Sidareja, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Ia merupakan putra kedua dari pasangan Kiai Zainal Arifin bin Kiai Darjan dan Nyai Sa’adah binti Kiai Asy’ari. Dari 15 bersaudara, hanya enam yang hidup hingga dewasa, termasuk KH Mukhdzir sendiri, sementara sembilan saudaranya wafat saat masih kanak-kanak.
Pada 1955, beliau menikah dengan Nyai Muryati binti H. Busyeri dari Sokaraja, Banyumas. Dari pernikahan ini, beliau dikaruniai sepuluh orang anak. Uniknya, seluruh anak-anak tersebut dinamai dengan awalan berdasarkan urutan huruf Hijaiyah, dari huruf alif hingga ra, yaitu:
1. Innarotul Umniyah (ا)
2. Barotun Naqiyah (ب)
3. Tasfiyatun Nadziroh (ت)
4. Tsabit Qoiddudin (almarhum) (ث)
5. Juned Anshori (almarhum) (ج)
6. Chasbulloh Siddiq (ح)
7. Khoirul Mawahib (خ)
8. Daimatul Maslahah (د)
9. Dzuriyatun Thoyyibah (ذ)
10. Roikhatul Jannah (ر)
Dalam bidang ma’isyah (penghidupan), KH Mukhdzir menjalani karier sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), dengan jabatan sebagai penghulu dan Kepala Urusan Agama (KUA) di sejumlah wilayah administratif di Kabupaten Cilacap. Penempatannya berpindah-pindah, di antaranya meliputi Cipari, Kawunganten, Sitinggil, Dayeuhluhur, dan Karangpucung. Mobilitasnya dalam menjalankan tugas pemerintahan dan dakwah dilakukan dengan menggunakan sepeda motor Zündapp, yang menjadi ciri khas perjalanannya dari satu lokasi pengajian ke lokasi lainnya.
Setelah beberapa waktu mengabdi sebagai aparatur negara, beliau memilih pensiun dini agar dapat lebih fokus dalam pengabdian kepada umat. Pada masa inilah KH Mukhdzir banyak menghasilkan karya-karya keilmuan, termasuk Kitab Tahlil Populer, yang menjadi salah satu warisan intelektual penting dan tersebar luas di kalangan Nahdliyin.
KH Mukhdzir wafat pada tanggal 26 November 2006 M, bertepatan dengan 5 Dzulqa’dah 1427 H. Kepergian beliau meninggalkan jejak keilmuan dan keteladanan yang mendalam bagi masyarakat dan lingkungan Nahdlatul Ulama di wilayah Cilacap dan sekitarnya.
Pendidikan
Pada masa kecilnya, KH Mukhdzir bin Zainal Arifin tergolong beruntung karena mendapatkan kesempatan untuk menempuh pendidikan formal setingkat Sekolah Rakyat (SR) yang setara dengan Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO), sebelum melanjutkan pendidikannya ke lingkungan pesantren.
Setelah menyelesaikan pendidikan dasar, beliau mulai menempuh perjalanan intelektual dengan belajar di berbagai pondok pesantren untuk mendalami beragam disiplin ilmu keislaman. Salah satu pesantren yang menjadi tempat persinggahan intelektual terlama bagi beliau adalah Pondok Pesantren Jampes di Kediri, yang kala itu diasuh oleh Syekh Ihsan dan kemudian dilanjutkan oleh putranya, Gus Malik.
Di Pesantren Jampes, KH Mukhdzir dikenal sebagai sosok santri yang tekun dan haus ilmu. Beliau tidak hanya rajin mengikuti pelajaran dari para kiai, tetapi juga memiliki kegemaran membaca yang sangat tinggi. Bahkan, setelah sesi pengajaran formal berakhir, beliau selalu menyempatkan diri untuk menyendiri dan membaca ulang materi yang telah diajarkan.
Kegemaran ini menjadi bagian penting dari proses pendalaman ilmu yang membuatnya tumbuh menjadi pribadi yang cerdas dan berwawasan luas. Ketekunan tersebut juga menjadikan beliau sebagai salah satu badal khatib andalan, yang kerap menggantikan khatib dalam pelaksanaan khutbah Jumat. Menariknya, beliau selalu menyampaikan khutbah tanpa membawa teks tertulis, sebuah kemampuan yang menunjukkan kekuatan daya ingat dan penguasaannya terhadap materi.
Selama menjadi santri di Bendo, KH Mukhdzir dikenal sebagai sosok santri yang menonjol secara intelektual, bahkan mendapat label sebagai santri “cerdas di atas rata-rata”. Salah satu pencapaiannya yang luar biasa adalah kemampuannya menyelesaikan bacaan kitab Iḥya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali dalam waktu yang relatif singkat dan secara berkala melakukan khataman berkali-kali dalam setahun.
Namun demikian, perjalanan intelektual KH Mukhdzir tidak selalu berjalan mulus. Sebagaimana para penuntut ilmu lainnya, beliau menghadapi berbagai ujian dan cobaan. Salah satu cobaan terberat yang pernah beliau alami adalah saat menderita penyakit kulit yang cukup parah hingga hampir menjalar ke seluruh tubuhnya.
Untuk mencegah penularan, pihak pesantren mengasingkan beliau ke sebuah kamar khusus yang letaknya terpisah dari “kombong” (asrama santri) lainnya. Meskipun dalam kondisi sakit dan terisolasi, KH Mukhdzir menunjukkan keteguhan hati, tetap tinggal di pesantren, dan menolak untuk pulang ke rumah.
Karya-karya dan Capaian
Tekad pensiun dini untuk berkhidmat kepada umat berbuah menghasilkan banyak karya ilmiah tertulis dalam bentuk kitab-kitab. Diantara nya yang telah dicetak, yaitu:
1. Kitab Tahlil Populer
2. Mahasina Shina'ah fi Tarjamahi Ahaditsi Ahlussunnah Waljama'ah
3. Nadhami Sapu Jagat Juz 1
4. Nadhami Sapu Jagat Juz 2
5. Tambah Arif fi Nadhami 'Ilmi Tashrif
6. Tanwirul Bashair fi Tarjamah Tafrihul Khathir Juz 1
7. Tanwirul Bashair fi Tarjamah Tafrihul Khathir Juz 2
8. Tanwirul Albab Fi tarjamati Fathil Wahhab
Adapun beberapa karya beliau yang belum sempat tercetak adalah;
1. Tanwirul Albab Fi tarjamati Fathil Wahhab,
2. Al hawi fi mandzumati ilmin nahwi,
3. Kitabul Haid, Kitabul Ikhtiar wa tawakkal.
4. An-nuqulul Lama’ah fi Dirasah Ahlis Sunnah wal Jama’ah
Kitab Tahlil Populer merupakan salah satu karya yang berisi panduan amaliah warga Nahdlatul Ulama (Nahdliyin), lengkap dengan penjelasan (taʿrīf) atas praktik-praktik keagamaannya. Kitab ini dikenal luas dan mengalami peredaran cetak yang sangat tinggi dibandingkan karya sejenis lainnya. Penyebarannya menjangkau berbagai wilayah di Indonesia, terutama di wilayah Karesidenan Banyumas, Kebumen, hingga Kediri, Jawa Timur.
Kitab Tahlil Populer, sebagai karya monumental KH Mukhdzir bin Zainal Arifin, juga menjadi wasilah spiritual yang sangat berarti dalam perjalanan hidup beliau. Tidak lama setelah kitab tersebut rampung disusun, di-tahqiq, dan mendapatkan taqridz dari dua ulama besar—yakni Romo KH Mustolih Badawie dari Kesugihan dan Syekh Syarwani dari Bendo, Pare Kediri—naskahnya kemudian diserahkan ke sebuah percetakan di Magelang untuk dicetak dan disebarluaskan. Proses penyusunan hingga penerbitan kitab ini menunjukkan keseriusan KH Mukhdzir dalam menjaga kualitas keilmuan dan validitas isi karyanya.
Melihat sambutan positif dari masyarakat dan tingginya permintaan, hak cipta Tahlil Populer kemudian dijual oleh KH Mukhdzir. Beliau mengambil keputusan ini dengan penuh kesadaran dan keikhlasan, karena merasa bahwa manfaat ilmu sudah tersebar luas dan kebutuhan pribadi telah terpenuhi.
Hasil dari penjualan hak cipta tersebut tidak hanya digunakan untuk membeli lahan persawahan, tetapi juga menjadi bekal bagi beliau untuk menunaikan ibadah haji bersama sang istri, Nyai Hj. Muryati. Perjalanan suci ini pun dijalani dengan penuh kesungguhan, bahkan mereka menetap di Tanah Suci selama enam bulan.
Kisah ini menjadi penanda bagaimana karya tulis yang lahir dari keikhlasan dan dedikasi pada umat, mampu membuka jalan bagi karunia besar dari Allah SWT. Ibadah haji pertama KH Mukhdzir tidak hanya merupakan pemenuhan rukun Islam kelima, tetapi juga bentuk nyata dari berkah ilmu yang ditulis dan diamalkan secara istiqamah.
Kitab lain, An-Nuqulul Lama’ah fī Dirāsah Ahlis Sunnah wal Jamā‘ah merupakan sebuah karya yang memuat pembahasan mendalam mengenai akidah Ahlus Sunnah wal Jama’ah. Kitab ini pernah diamanahkan kepada Kiai Hayatul Bahri Mbakung, putra dari Kiai Solehan Syamsuddin, dengan maksud agar disampaikan kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Tujuannya adalah agar kitab tersebut segera dicetak secara resmi dan memperoleh legalitas dari PBNU sebagai rujukan keilmuan dalam bidang akidah.
Sebagai bagian dari proses validasi ilmiah, kitab ini juga telah disowankan (dipresentasikan) kepada beberapa dzurriyah (keturunan) ulama terkemuka, khususnya kepada dzurriyah Syekh Ihsan Jampes Kediri, antara lain kepada KH Munif dan KH Busyro.
Salah satu tujuan utama sowan tersebut adalah untuk memohon koreksi (tashih) serta pengesahan berupa kata pengantar atau rekomendasi (taqrīẓ) dari para ulama tersebut. Namun, sebelum proses tashih dilakukan oleh KH Munif, beliau wafat terlebih dahulu. Selain itu, karena berbagai kendala lainnya, hingga kini kitab An-Nuqulul Lama’ah masih belum diterbitkan secara resmi.
Menurut penuturan para senior dan keluarganya, latar belakang dari lahirnya karya-karya KH Mukhdzir bin Zainal Arifin tak dapat dilepaskan dari pengalaman spiritual yang beliau alami semasa mondok di Pesantren Bendo, Kediri. Saat itu, beliau pernah mengalami ujian kesehatan yang sangat berat, hingga oleh sebagian orang dianggap akan segera wafat. Namun, di akhir masa sakit tersebut, seorang kiai menyampaikan kepadanya bahwa kondisi yang dialaminya bukanlah penyakit semata, melainkan sebuah imtihan (ujian) dari Allah SWT untuk menguatkan dirinya.
Pada penghujung ujian tersebut, KH Mukhdzir menerima sebuah pertanyaan yang bersifat spiritual dan menentukan arah pengabdiannya di masa depan: “Apakah engkau ingin memiliki banyak santri atau memiliki ilmu yang luas dan mendalam?” Beliau menjawab dengan mantap, “ilmu.”
Kisah ini diriwayatkan oleh Gus Sarwani dari Bendo, dan menjadi titik awal dari semangat KH Mukhdzir dalam mendokumentasikan dan menyalurkan ilmunya melalui karya-karya tulis, agar senantiasa bermanfaat bagi umat lintas generasi. Ini pula yang menjelaskan mengapa beliau tidak membangun pesantren besar dengan ribuan santri, melainkan memilih jalan pengabdian melalui tulisan dan pengajaran intensif.
Santri-santri yang mengaji langsung kepada KH Mukhdzir umumnya merupakan para gus dan kiai muda dari berbagai daerah. Mereka tabarukan untuk mengaji kitab-kitab lanjutan seperti kitab Buhgyatul Musytarsyidin, Alfiyah ibn Malik, Fathul Qarib, Mizanul Kubro, dan masih banyak lagi.
Dalam catatan keluarga, terdapat sejumlah nama yang tercatat sebagai murid langsung beliau, di antaranya adalah: Kiai Mustangirun (penghulu Cipari), Kiai Yazid, Kiai Muhail (dari Patimuan), Kiai Sodiqin, dan seorang kiai yang namanya tidak tercatat.
Kelima kiai tersebut biasa mengikuti pengajian dari KH Mukhdzir pada jam 09.00 hingga 11.00 pagi secara rutin. Selain itu, tercatat pula nama-nama lain seperti: Kiai Mujib, Kiai Tefur (atau Yajid), Kiai Krisik, Kiai Sipon, Kiai Nano, Kiai Tuhfatul Murid, Kiai Mandiri, dan Kiai Hayatul Maki.
Terdapat pula kisah lain mengenai tiga santri yang awalnya hendak berguru kepada KH Mustolih Badawi. Namun, oleh beliau justru disarankan untuk mengaji kepada KH Mukhdzir. Ketiga santri tersebut adalah KH Dahroni, KH Munawar, dan KH Shohib. Awalnya mereka tinggal di ndalem (rumah kiai), namun karena kehadiran mereka cukup menetap, akhirnya KH Mukhdzir membangunkan kamar atau ruang khusus yang kemudian berfungsi sebagai semacam pondok sederhana untuk mereka tinggali.
Selain itu, lima orang gus dari Bendo juga tercatat mengaji langsung kepada KH Mukhdzir. Mereka adalah Gus Basith, Gus Munif, Gus Nuh, Gus Khotim, Gus Yunus.
Kisah dan pola pengajaran tersebut menunjukkan bahwa meskipun KH Mukhdzir tidak memiliki pesantren besar secara fisik, beliau tetap menjadi magnet keilmuan dan rujukan penting bagi para calon ulama muda. Metode pengajaran beliau yang personal dan fokus menjadikan proses transfer ilmu lebih mendalam dan berkesan, baik secara intelektual maupun spiritual.
Sebagai seorang ulama sekaligus pendidik, KH Mukhdzir bin Zainal Arifin tidak hanya meninggalkan warisan dalam bentuk karya-karya tulis, tetapi juga dalam bentuk metode pendidikan yang khas dan efektif. Salah satu pendekatan pendidikan yang beliau terapkan dapat disebut sebagai metode pembiasaan, yakni dengan membangun rutinitas kegiatan santri yang konsisten dan terarah. Rutinitas ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga memiliki dimensi pedagogis dan spiritual yang kuat.
Salah satu bentuk konkret dari metode pembiasaan ini adalah kegiatan rutin para santri setelah melaksanakan shalat Maghrib berjamaah. Dalam durasi sekitar 15 menit, para santri berkumpul untuk mengikuti kegiatan hafalan bersama yang dipandu langsung oleh KH Mukhdzir.
Dalam kegiatan ini, beliau melafalkan ayat-ayat Al-Qur’an, wirid, atau doa-doa tertentu yang kemudian diikuti serempak oleh para santri. Bacaan diulang beberapa kali untuk memperkuat memori, dan secara acak, santri akan ditunjuk untuk melafalkan kembali bacaan yang telah diulang-ulang sebelumnya. Teknik ini tidak hanya melatih kesiapan mental dan konsentrasi para santri, tetapi juga secara perlahan menanamkan hafalan tanpa tekanan yang berlebihan.
Selain itu, untuk menjaga semangat dan suasana yang menyenangkan, hafalan seringkali diselingi dengan lantunan nadzoman atau shalawatan, yang turut memperkaya dimensi estetika dan spiritualitas para santri.
Hasil dari metode ini sangat nyata. Para santri berhasil menghafal Juz ‘Amma, surat-surat penting dalam Al-Qur’an, serta berbagai wirid dan doa-doa harian. Ini menunjukkan bahwa KH Mukhdzir tidak hanya mengajarkan ilmu secara teoritis, tetapi juga membentuk karakter dan kebiasaan melalui pendekatan yang sistematis dan berkesinambungan.
Ketekunan dan kedisiplinan dalam mendidik juga tercermin dalam cara beliau mengajar anak-anaknya sendiri. Menurut kesaksian putri sulungnya, KH Mukhdzir dikenal sebagai sosok pengajar yang tegas, bahkan cenderung “galak”. Sang putri mengisahkan, “Nek mulang aku ngaji ba’da Maghrib, hari berikutnya kudu apal” (Kalau beliau mengajar saya ngaji setelah Maghrib, maka besoknya saya harus hafal). Hal ini menunjukkan bahwa disiplin dan target capaian hafalan tidak hanya diterapkan kepada santri umum, tetapi juga kepada keluarga beliau sendiri.
Metode pendidikan KH Mukhdzir ini merupakan bagian integral dari warisan intelektual dan spiritual beliau. Bukan hanya dalam bentuk kitab-kitab yang beliau tulis, tetapi juga dalam bentuk living tradition pendidikan Islam yang membentuk karakter generasi penerus dengan pendekatan yang aplikatif dan menyentuh hati. Hal ini menjadikan beliau bukan hanya seorang ulama penulis, tetapi juga pendidik sejati yang mewariskan metode yang efektif dan kontekstual hingga kini.
Pengajian Keislaman dan Khidmah
Setelah boyong (kembali ke rumah) dari menimba ilmu di Pondok Pesantren Jampes, Kediri, KH Mukhdzir melanjutkan pengabdiannya di tengah masyarakat. Pada masa awal setelah kepulangan dari pesantren, beliau berkhidmah bersama ayahandanya, Kiai Zainal Arifin, dalam mendampingi masyarakat sekitar. KH Mukhdzir dikenal sebagai sosok yang istiqamah dalam menerapkan prinsip amaliyah ilmiyah—yakni mengamalkan ilmu yang dimiliki secara nyata dalam kehidupan sehari-hari.
Di wilayah Cilacap bagian barat, yang pada waktu itu dikenal sebagai kawasan dengan nuansa keagamaan yang masih kental dengan tradisi abangan, keberadaan ulama sangat terbatas. Dalam konteks ini, KH Mukhdzir tampil sebagai pelopor dakwah dan syiar Islam. Bersama dua sahabat seperjuangannya, yaitu KH Syamsudin dan Kiai Romlan Al-Junaidi, beliau dikenal sebagai bagian dari “tiga serangkai” pejuang Nahdlatul Ulama (NU) di daerah tersebut.
Gerakan dakwah yang dilakukan pada masa mudanya sering disebut dengan istilah babad alas—yakni membuka wilayah baru untuk dakwah Islam. Tidak lama kemudian, perjuangan dakwah ini turut melibatkan adik beliau, KH Ma’mun Arifin, yang kemudian ikut memperkuat gerakan keulamaan di kawasan tersebut.
Salah satu kontribusi besar KH Mukhdzir terhadap masyarakat adalah inisiatifnya dalam mendirikan masjid. Sekitar tahun 1984, atas dorongan dari para ikhwan dan warga sekitar, beliau memprakarsai pembangunan masjid jami’ di Dusun Pagergunung, Desa Cipari, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah yang pada saat itu belum memiliki fasilitas untuk pelaksanaan salat Jumat. Setelah melalui proses musyawarah dan kerja sama dengan masyarakat, pembangunan masjid pun dimulai. Ketika masjid tersebut berdiri, KH Mukhdzir menamainya dengan As-Sa’adah, sebagai bentuk tafa’ul (pengambilan berkah nama) dari nama ibunda beliau, Nyai Sa’adah.
Dalam mengelola masjid, KH Mukhdzir menunjukkan sikap kehati-hatian (ihtiyath), terutama dalam memastikan terpenuhinya syarat sah salat Jumat menurut mazhab Syafi’i yang mensyaratkan kehadiran minimal 40 jamaah. Beliau menugaskan salah satu santri kalong (santri dari dusun), bernama Pak Zuhri, untuk menghitung jumlah jama’ah yang hadir pada setiap pelaksanaan salat Jumat di masa awal operasional masjid.
Seiring berjalannya waktu, Masjid As-Sa’adah tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah salat, tetapi juga berkembang menjadi pusat pendidikan dan dakwah masyarakat. Berbagai pengajian diselenggarakan, termasuk pengajaran agama bagi anak-anak, yang memperluas peran sosial dan keagamaan masjid tersebut. Hal ini secara tidak langsung menambah intensitas tanggung jawab KH Mukhdzir dalam kesehariannya, baik sebagai ulama, pendakwah, maupun pembina masyarakat.
Aktivitas Sosial Politik dan Budaya
Selain dikenal sebagai ulama yang alim dan kharismatik, KH Mukhdzir bin Zainal Arifin juga memiliki performed fisik (penampilan fisik) yang khas dan berwibawa. Kepribadian beliau yang tegas namun bersahaja, dipadu dengan gestur dan intonasi bicara yang kuat, membuatnya mencerminkan sosok pemimpin dengan karisma yang menonjol.
Dalam sebuah kesempatan, bahkan sempat muncul tawaran dari pihak perfilman untuk menjadikan KH Mukhdzir sebagai pemeran utama dalam film dokumenter sejarah nasional G30S/PKI guna memerankan tokoh Presiden Soekarno. Hal ini menunjukkan bahwa wibawa dan citra publik beliau begitu kuat, hingga dianggap mampu merepresentasikan sosok proklamator bangsa di layar lebar.
Meskipun tawaran tersebut tidak dilanjutkan, fakta ini menjadi salah satu indikasi kuat bahwa figur KH Mukhdzir bukan hanya dihormati dalam ranah keilmuan dan keulamaan, tetapi juga memiliki daya tarik visual dan karakteristik kepemimpinan yang diakui secara luas, baik di lingkungan pesantren maupun oleh masyarakat umum.
Roikhatul Jannah, Pengurus Pimpinan Pusat Fatayat Nahdlatul Ulama
Terpopuler
1
KH Thoifur Mawardi Purworejo Meninggal Dunia dalam Usia 70 tahun
2
Targetkan 45 Ribu Sekolah, Kemendikdasmen Gandeng Mitra Pendidikan Implementasi Pembelajaran Mendalam dan AI
3
Kuasa Hukum Rakyat Pati Mengaku Dianiaya hingga Disekap Berjam-jam di Kantor Bupati
4
Amalan Mengisi Rebo Wekasan, Mulai Mandi, Shalat, hingga Yasinan
5
Ramai Kritik Joget Pejabat, Ketua MPR Anggap Hal Normal
6
Pimpinan DPR Bantah Gaji Naik, tapi Dapat Berbagai Tunjangan Total hingga Rp70 Juta
Terkini
Lihat Semua