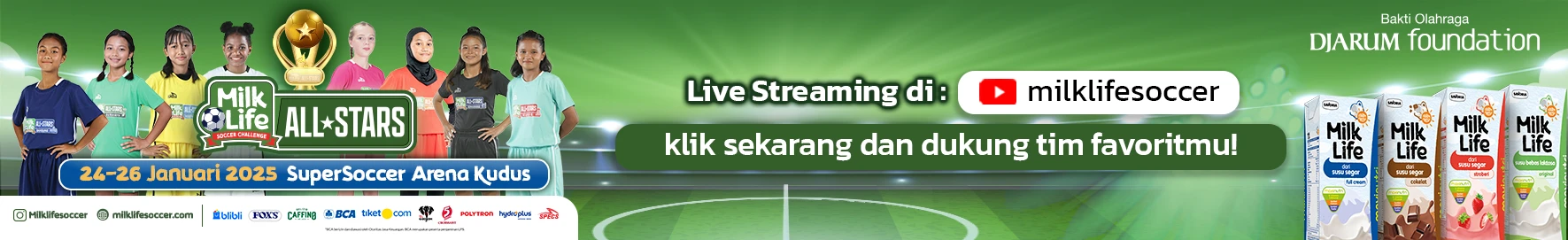Oleh Fathoni Ahmad
Lembaga pendidikan pesantren didirikan tidak hanya berawal dari tujuan mensyiarkan ilmu-ilmu agama Islam, tetapi juga wadah kegiatan sosial-kemasyarakatan, termasuk sebagai wadah pergerakan nasional kemerdekaan melawan penjajah. Pesantren tersebut membuat pesantren tidak lepas dari akar sosial masyarakatnya. Tradisi dan amaliyah keagamaan yang berkembang di pesantren juga dipraktikkan oleh masyarakat.
Ulama pesantren dijadikan simbol akhlak dengan segala kearifan dan kebijaksanaannya. Mereka membawa ajaran-ajaran yang diwariskan oleh Nabi Muhammad SAW. Nasihatnya didengar, petuahnya direnungkan, dan fatwanya diikuti. Bukan bertujuan mengkultuskan pribadi manusia, melainkan karena akhlak mulia dan kedalaman ilmunya. Kearifan kiai memunculkan keluhuran tradisi pesantren yang hingga kini berkembang di tengah masyarakat luas.
Jauh daripada itu, para ulama pesantren berjuang atas dasar kemaslahatan bangsa, bahkan skala global. Prinsip kemerdekaan bangsa yang akan memunculkan kemaslahatan bersama harus diperjuangkan bersama-sama. Ulama pesantren berperan sebagai penggerak rakyat melawan penjajah. Bahkan selain sebagai tempat menempa ilmu-ilmu agama dan wadah pergerakan nasional, pesantren juga sebagai tempat penyemaian kecintaan santri dan masyarakat terhadap bangsa dan negaranya.
Pada titik itulah kearifan dalam memandang kepentingan bangsa menjadi tolak ukur perjuangan para ulama pesantren beserata santri-santrinya. Mereka berhasil mendudukkan bersama antara prinsip keagamaan dengan konsep berbangsa dan bernegara dalam irama persatuan sebagai modal penting melawan penjajah. Dalam kondisi terjajah, prinsip kecintaan tanah air merupakan aktualisasi nilai-nilai agama sehingga perjuangan memerdekakan bangsa Indonesia merupakan panggilan agama.
Prinsip tersebut menyublim pada diri KH Muhammad Hasyim Asy’ari (Pendiri NU) sehingga lahir konseptualisasi agung hubbul wathoni minal iman (cinta tanah air adalah bagian dari iman). Istilah iman di sini tidak hanya berlaku bagi umat Islam, tetapi juga konsep iman menurut keyakinan dan agama-agama lain di luar Islam. Dampaknya, konsep tersebut tidak hanya menggelorakan perjuangan umat Islam, tetapi juga umat-umat agama lain beserta seluruh bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari kungkungan penjajah.
Tentang sosok Kiai Hasyim Asy’ari, ia menempa diri dalam pencarian ilmu di Makkah tidak lantas membuat Hadhratussyekh Muhammad Hasyim Asy’ari (1871-1947) alpa terhadap keadaan dan kondisi bangsanya. KH Hasyim Asy’ari merupakan pemegang sanad ke-14 dari Kitab Shahih Bukhori Muslim. Keilmuan agama ia perdalam di tanah hijaz dan banyak berguru dari ulama kelahiran Nusantara di Makkah seperti Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Mahfudz Termas, Syekh Yasin Al-Fadani, dan ulama-ulama lainnya.
Sebutan hadlratussyekh sendiri menggambarkan bahwa ayah KH Wahid Hasyim tersebut merupakan mahaguru, mahakiai. Bahkan, Muhammad Asad Syihab (1994) menyebut Kiai Hasyim dengan sebutan al-‘Allamah. Dalam tradisi Timur Tengah, istilah tersebut diberikan kepada orang yang mempunyai pangkat keulamaan dan keilmuan yang tinggi.
Zamakhsyari Dhofier dalam Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kiai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia (2011) mencatat, dalam tradisi pesantren dikenal sistem ijazah yang bentuknya tidak seperti yang masyarakat kenal dalam sistem sekolah. Ijazah model pesantren berbentuk pencantuman nama dalam suatu daftar rantai transmisi pengetahuan yang dikeluarkan oleh gurunya terhadap muridnya yang telah menyelesaikan pelajaran dan ilmu dengan baik tentang buku atau kitab tertentu. Dari sanad yang disahkan melalui ijazah itu, seorang murid dianggap telah menguasai dan punya otoritas mengajarkan ilmu tersebut kepada orang lain.
Tradisi ijazah ini hanya dikeluarkan untuk murid-murid tingkat tinggi dan hanya mengenai kitab-kitab besar dan masyhur. Para murid yang telah mencapai tingkat yang cukup tinggi disarankan untuk membuka pengajian, sedangkan yang memiliki ijazah biasanya dibantu untuk mendirikan pesantren.
Namun, seperti disebutkan di awal, meskipun Kiai Hasyim Asy’ari mumpuni dalam ilmu agama, tetapi ia tidak menutup mata terhadap bangsa Indonesia yang masih dalam kondisi terjajah. Kegelisahaannya itu dituangkan dalam sebuah pertemuan di Multazam bersama para sahabat seangkatannya dari Afrika, Asia, dan juga negara-negara Arab sebelum Kiai Hasyim kembali ke Indonesia.
Pertemuan tersebut terjadi pada suatu di bulan Ramadhan, di Masjidil Haram, Makkah. Singkat cerita, dari pertemuan tersebut lahir kesepakatan di antara mereka untuk mengangkat sumpah di hadapan “Multazam”, dekat pintu ka’bah untuk menyikapi kondisi di negara masing-masing yang dalam keadaan terjajah.
Isi kesepakatan tersebut antara lain ialah sebuah janji yang harus ditepati apabila mereka sudah sampai dan berada di negara masing-masing. Sedangkan janji tersebut berupa tekad untuk berjuang di jalan Allah SWT demi tegaknya agama Islam, berusaha mempersatukan umat Islam dalam kegiatan penyebaran ilmu pengetahuan serta pendalaman ilmu agama Islam.
Bagi mereka, tekad tersebut harus dicetuskan dan dibawa bersama dengan mengangkat sumpah. Karena pada saat itu, kondisi dan situasi sosial politik di negara-negara Timur hampir bernasib sama, yakni berada di bawah kekuasaan penjajahan bangsa Barat. (Choirul Anam, Pertumbuhan dan Perkembangan NU, 2010)
Perhatian para kiai terhadap bangsanya tak hanya berhenti dalam perjuangan pemikiran dan fisik, tetapi juga menyiapkan dan menempa para generasi muda untuk mencintai bangsanya. Hal ini dilakukan oleh KH Abdul Wahab Chasbullah saat menginisiasi gerakan-gerakan pemuda cinta tanah air melalui Madrasah dan Perguruan Nahdlatul Wathan pada tahun 1916.
Konsep cinta tanah air melalui pendidikan ini menyadarkan para generasi muda agar bersatu melawan penjajah demi kemerdekaan bangsa Indonesia. KH Wahab Chasbullah berhasil mendirikan perguruan Nahdlatul Wathan atas bantuan beberapa kiai lain dengan dirinya menjabat sebagai Pimpinan Dewan Guru (keulamaan). Sejak saat itulah Nahdlatul Wathan dijadikan markas penggemblengan para pemuda. Mereka dididik menjadi pemuda yang berilmu dan cinta tanah air.
Bahkan setiap hendak dimulai kegiatan belajar, para murid diharuskan terlebih dahulu menyanyikan lagu perjuangan dalam bahasa Arab ciptaan Mbah Wahab sendiri. Kini lagu tersebut sangat populer di kalangan pesantren dan setiap kegiatan Nahdlatul Ulama (NU), yakni Yaa Lal Wathan yang juga dikenal dengan Syubbanul Wathan. Benih-benih cinta tanah air ini akhirnya bisa menjadi energi positif bagi rakyat Indonesia secara luas sehingga perjuangan tidak berhenti pada tataran wacana, tetapi pergerakan sebuah bangsa yang cinta tanah airnya untuk merdeka dari segala bentuk penjajahan.
Semangat nasionalisme Kiai Wahab yang berusaha terus diwujudkan melalui wadah pendidikan juga turut serta melahirkan organisasi produktif seperti Tashwirul Afkar (gerakan pencerahan) yang berdiri tahun 1919 dan Nahdlatut Tujjar (gerakan kemandirian ekonomi). Selain itu, terlibatnya Kiai Wahab di berbagai organisasi pemuda seperti Indonesische studie club, Syubbanul Wathan, dan kursus Masail Diniyyah bagi para ulama muda pembela madzhab tidak lepas dari kerangka tujuan utamanya, membangun semangat nasionalisme bangsa Indonesia yang sedang terjajah.
Dalam mengembangkan Madrasah Nahdlatul Wathan dan Tashwirul Afkar ini, Kiai Wahab berupaya menyebarkan 'virus' cinta tanah air (hubbul wathan) secara luas di tengah masyarakat dengan membawa misi tradisi keilmuan pesantren. Perjuangan mulia ini tentu harus digerakkan secara terus-menerus melalui setiap lembaga pendidikan yang ada saat ini sehingga cita-cita luhur pendiri bangsa untuk memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) semakin kuat dan tak pernah surut.
Kiai Hasyim Asy’ari dan Kiai Wahab Chasbullah merupakan dua ulama pesantren di antara banyak kiai-kiai lain yang aktif dalam pergerakan nasional untuk memerdekakan bangsa Indonesia. Hal itu menunjukan bahwa kedalaman ilmu agama dengan pemahaman yang baik dan benar yang berasal dari ilmunya para ulama dapat menumbuhkan kearifan bangsa. Kesemuanya itu tidak lepas dari keluhuran tradisi pesantren.
Penulis adalah Redaktur NU Online