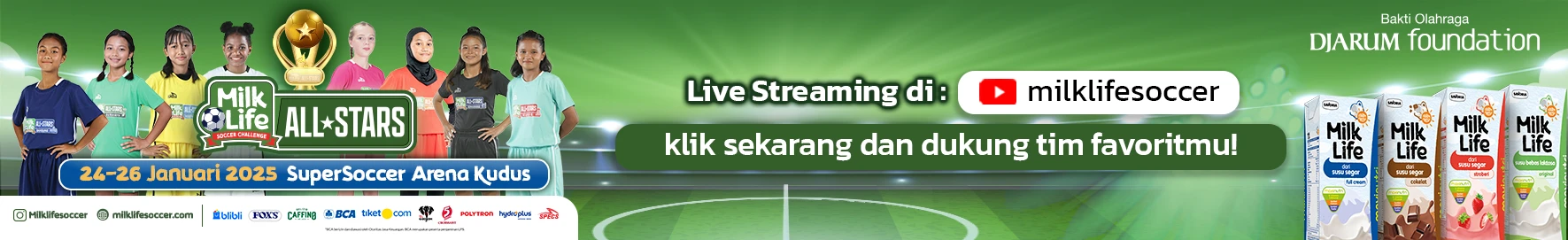Oleh Achmad Faiz MN Abdalla
Pondok pesantren dan madrasah diniyah itu benteng. Setiap desa idealnya punya benteng. Kalau tidak, berarti tak ada pertahanan. Bisa jebol dengan gampang. Kasihan masyarakat –Kiai Mahsun Masyhudi
Sepenggal petuah itu didapat Kang Rijal Mumazziq, Ketua LTN PCNU Surabaya, saat ia berkunjung ke rumah almaghfurlah Kiai Mahsun di Ujungpangkah, Gresik. Semasa hidup, Kiai Mahsun merupakan pendiri sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Mambaul Ihsan Ujungpangkah, Gresik, dan tercatat pernah menjabat wakil rais syuriyah PCNU Gresik.
Petuah itu menarik buat saya, terutama bila dikaitkan dengan keadaan di Gresik utara saat ini. Setelah nyantri di Kiai Maksum Lasem, seluruh hidup Kiai Mahsun dicurahkan untuk masyarakat, tepatnya masyarakat Ujungpangkah dan pesisir Gresik utara. Karena itu, tutur dan pemikirannya sedikit banyak merupakan refleksi atas keadaan sosial yang dilihat dan dirasakannya.
Seiring gencarnya industrialisasi di pesisir Gresik utara, terjadi pergeseran cepat dari masyarakat pesisir-agraris ke masyarakat industri. Tradisi-tradisi NU yang selama ini melekat, pun terkena imbasnya. Padahal tradisi-tradisi tersebut menjadi pilar pendidikan karakter. Di sinilah, pesantren dirasakan semakin penting hadirnya sebagai benteng paham dan tradisi NU.
Kenyataannya, tidak semua desa atau ranting NU mempunyai pondok pesantren. Maka seperti dikatakan Kiai Mahsun, tidak ada benteng atau pertahanan. Bilapun ada, benteng itu tidak kuat. Yang terjadi kemudian, tradisi dan sendi-sendi paham aswaja NU mulai keropos seiring pergeseran masyarakat. Hal itu pada gilirannya akan mengikis pendidikan karakter.
Pesantren sebagai kultur
Lantas bagaimana untuk desa atau ranting NU yang belum memiliki pesantren? Tentu banyak faktor, mengapa sebuah desa tidak memiliki pesantren. Salah satunya, faktor sumberdaya manusia. Di desa kami misal, rata-rata masyarakatnya hanya alumni madrasah di desa, bukan pesantren, sehingga kemampuannya membaca kitab kuning kurang. Hal itu yang nampaknya menjadi alasan, kurang beraninya masyarakat untuk mendirikan pesantren.
Namun meski tidak ada pondok pesantren, saya menangkap adanya kultur pesantren dalam proses pendidikan sehari-hari. Desa kami memiliki madrasah, langgar dan masjid sebagai basis pendidikan formal dan agama. Madrasah sebagai basis pendidikan formal. Di luar itu, masjid dan langgar secara bergantian sebagai basis pendidikan diniyah, belajar mengaji Al-Qur’an serta tempat diselenggaranya tradisi keagamaan.
Sehari-hari, para pelajar dilingkupi tiga basis pendidikan tersebut. Pagi mereka menjalani sekolah formal di madrasah. Sore mereka belajar di diniyah. Malamnya mereka mengaji di langgar. Dari pagi sampai malam, secara bergantian mereka dinaungi atap pendidikan yang berbeda.
Tidak berhenti di situ, NU ranting setempat juga sangat memperhatikan keberadaan IPNU sebagai auxiliary system di luar primary system ketiga basis pendidikan di atas. Para pelajar sangat ditekankan untuk aktif di IPNU guna belajar berorganisasi, menempa kepekaan sosialnya, dan ditanamkan nilai-nilai keluhuran serta ajaran aswaja melalui tradisi.
Gagasan Pesantren Sosial
Menurut saya, baik pesantren maupun pendidikan karakter memiliki persamaan prinsip, yakni pendidikan utuh yang mengintegrasikan empat dimensi pengolahan hidup manusia, meliputi olah hati, olah pikir, olah rasa, dan olah raga. Dalam konsepsi Perpres 87/2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter, pendidikan utuh tersebut diwujudkan melalui tripusat pendidikan, yakni sinergi antara keluarga, sekolah, dan masyarakat.
Bila dipadatkan lagi, pengertian keduanya adalah pendidikan yang melingkupi pelajar sejak ia bangun sampai ia tidur, sehingga tidak hanya terbatas pada pendidikan formal di sekolah. Karena itu, pesantren dan pendidikan karakter memiliki kesamaan prinsip.
Yang membedakan adalah operasionalnya. Pesantren identik dengan menetap. Seorang pelajar yang menetap di pondok disebut santri. Sehari-hari ia dididik dan diasuh oleh sang kiai. Sedang pendidikan karakter, seperti yang dikonsepkan Perpres PPK, adalah pendidikan utuh dalam sinergitas peran keluarga, sekolah dan masyarakat.
Karena itu menurut saya, pendidikan karakter seperti di atas merupakan pesantren dalam arti sosial (pesantren sosial). Pesantren sosial dimengerti sebagai kultur atau praktik pendidikan yang memadukan keluarga, sekolah dan masyarakat. Maka bagi desa yang belum mampu mendirikan pondok pesantren, pesantren dalam arti sosial perlu disadari arti pentingnya untuk mewujudkan pendidikan karakter.
Dalam gagasan pesantren sosial, sinergi madrasah dengan masjid dan langgar sebagai alam perguruan akan menjadi sendi utama. Karenanya, bila salah satu sendi itu keropos, harus segera dipikirkan bersama agar kokoh kembali. Lunturnya tradisi langggar, misal, tidak boleh dibiarkan, karena langgar memiliki peran sangat penting sebagai sendi pendidikan agama, paham serta tradisi masyarakat.
Di luar itu, masyarakat dan keluarga juga harus mulai menyadari arti pentingnya sebagai bagian tripusat pendidikan. Pendidikan bukan hanya urusan alam perguruan atau sekolah. Terbangun tidaknya pendidikan karakter dengan kokoh juga sangat ditentukan peran keluarga sebagai unit pendidikan terkecil dan masyarakat sebagai alam pergerakan. Keropos salah satu, akan merusak tripusat pendidikan lainnya.
Selanjutnya di masyarakat atau alam pergerakan itu, IPNU memainkan perannya. Tidak boleh ada kekosongan pendidikan di masyarakat. Lingkungan masyarakat akan sangat mempengaruhi proses pendidikan. Maka, IPNU perlu dihadirkan untuk mengisi peran pendidikan di masyarakat. Baik NU, pemerintah setempat, juga IPNU sendiri perlu menyadari itu. Inilah yang saya maksud IPNU dalam gagasan pesantren sosial.
Peran IPNU
Setidaknya, ada dua fungsi penting yang diemban IPNU dalam gagasan pesantren sosial tersebut. Pertama, IPNU harus menjadi agen tradisi. Maraknya kenakalan remaja, bahkan intolerasi dan radikalisme dewasa ini, adalah bukti tidak berdirinya pendidikan di atas infrastruktur budaya. Pendidikan direduksi hanya sebagai alam perguruan di sekolah formal. Sementara pembelajaran nilai-nilai luhur semakin terkikis.
Di sinilah tradisi mempunyai dalih untuk diperkuat. Tradisi merupakan tempat dimana nilai-nilai luhur disimbolkan. Di sekolah-sekolah formal, nilai-nilai tersebut juga diajarkan oleh guru kepada muridnya. Namun oleh pendahulu kita, agar nilai-nilai tersebut mudah diingat serta hidup dalam kebiasaan masyarakat, maka disampaikan dan ditanamkan melalui tradisi.
Ruang kelas dan tradisi sejatinya sama, karena menjadi media untuk mengomunikasikan nilai-nilai tersebut. Namun bedanya, bila ruang kelas sekadar bersifat teoritis-normatif, maka tradisi bersifat dinamis-sosiologis. Melalui tradisi, nilai-nilai yang abstrak itu menjadi hidup. Karena itu, IPNU harus menjadi penggerak tegaknya tradisi tersebut.
Kedua, IPNU sebagai basis berorganisasi dan bermasyarakat bagi pelajar. Berorganisasi adalah basis praktik bagi pelajar sehingga pelajar tidak terbatasi sempitnya ruang kelas. Melalui organisasi, pelajar akan melampaui sekat-sekat ruang kelas dengan belajar berinteraksi, mengomunikasikan idenya ke orang lain, dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama.
Di organisasi, wawasan seseorang pelajar akan semakin luas. Selain karena ia terbiasa menerima ide orang lain, ia pun akan menjangkau pengetahuan sebagai praktik, selain pengetahuan sebagai teori. Maka, cara berpikir seorang pelajar yang berorganisasi akan menunjukkan komprominya terhadap teori dan praktik.
Di IPNU juga, para pelajar menemukan lorong untuk merasakan berinteraksi dengan masyarakat. Maka tidak heran, pelajar yang gemar berorganisasi memiliki keberanian dan kemampuan public speaking yang terasah. Hal itu penting untuk mulai membekalinya kemampuan bermasyarakat. Bagaimanapun, IPNU merupakan organisasi kader untuk menempa para pelajar agar nantinya menjadi pribadi yang mumpuni di masyarakat.
Terutama di era pembangunan desa sekarang, IPNU di ranting-ranting harus mulai berpartisipasi. Kemampuan organisasi yang diasahnya di IPNU dapat ditransformasikan untuk berkiprah dalam pembangunan desa, terutama untuk memperkuat peran masyarakat. Apalagi banyak yang menengarai, belum tercapainya maksud-maksud pokok UU Desa disebabkan lemahnya SDM.
Penulis adalah Pelajar NU Gresik, Jawa Timur.