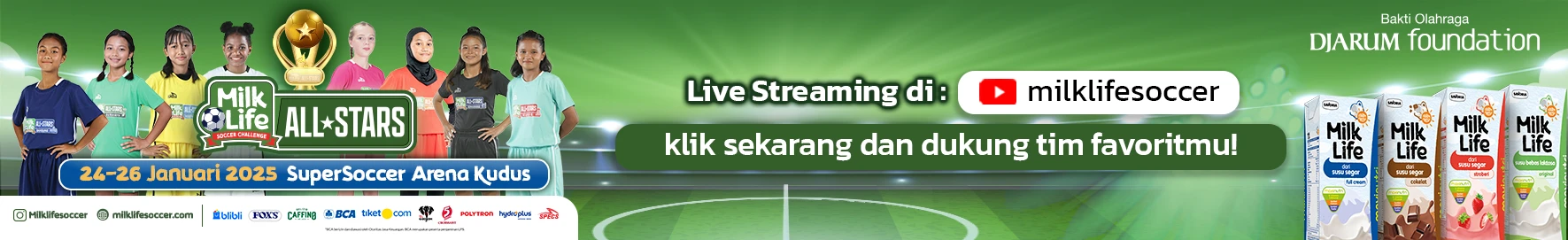Oleh: Achmad Faiz MN Abdalla
Dalam catatan Ahmad Erani Yustika (Kompas, Opini, 23/10), sejauh yang sudah tercapai selama dua tahun pelaksanaan program dana desa, sekurangnya lima hal pokok telah dirasakan di lapangan. Pertama, desa berdenyut kembali dalam kegairahan pembangunan yang ditandai oleh maraknya kegiatan musdes dan keterlibatan warga dalam perencanaan sampai eksekusi pembangunan. Kedua, transparansi anggaran menjadi keniscayaan baru sebagai bagian dari akuntabilitas penyelenggara pemerintahan desa.
Ketiga, keswadayaan dan gotong royong terlihat kokoh karena seluruh program harus dijalankan secara swakelola, tak boleh diberikan kepada pihak ketiga. Keempat, munculnya aneka upaya memperkuat kapasitas warga dan pemberdayaan lestari dengan basis budaya dan pengetahuan lokal. Banyak desa yang menginisiasi munculnya sekolah desa, sekolah perempuan, peraturan desa untuk memproteksi sumber daya alam dan ekologi, pembuatan almanak desa, balai rakyat dan masih banyak lagi prakarsa lain.
Kelima, ongkos pembangunan menjadi amat murah karena dikerjakan oleh warga desa dengan semangat keguyuban. Pada 2016 lalu, terbangun hampir 67.000 km jalan, jembatan 511,9 km, dan PAUD 11.926 unit. Dana desa juga dimanfaatkan untuk posyandu 7.524 unit, polindes 3.133 unit, dan sumur 14.034 unit. Dana desa juga digunakan untuk pembangunan tambatan perahu 1.373 unit, pasar desa 1.819 unit, embung 686 unit, drainase 65.998 unit, irigasi 12.596 unit, penahan tanah 38.184 unit, dan ribuan BUMDes (PPMD, 2017).
Namun, harus diakui, meski penyerapan anggaran terbilang tinggi, yakni tahun pertama 82,72 persen dan tahun kedua 97,65 persen, dana desa sangat berpotensi menjadi sumber korupsi baru. ICW mencatat peningkatan kasus korupsi terkait dengan pengelolaan anggaran desa, yakni sekitar 106 kasus yang terjadi sepanjang 2015 sampai September 2017. Jumlah tersebut belum termasuk banyaknya laporan dugaan penyimpangan dana desa lainnya yang mencapai 600 di Satgas Dana Desa hingga periode Juli 2017.
Untuk itu, pada 20 Oktober lalu, tiga institusi negara yakni Kementerian Desa PDTT, Kementerian Dalam Negeri dan Kepolisian Rebuplik Indonesia sepakat mengawasi jalannya penggunaan dana desa di seluruh desa se-Indonesia. Inti dari kerjasama itu untuk mengawasi penggunaan dana desa yang jumlahnya kian meningkat dari tahun ke tahun. Maka, sejak kesepakatan ditandatangani, Kepolisian punya wewenang melakukan pengawasan dan bisa melakukan penanganan jika terjadi permasalahan penggunaan dana desa.
Beroperasinya Hukum
Ada beberapa faktor yang menentukan proses penegakan hukum, sebagaimana diungkapkan oleh Friedman (1998:44), yaitu subtansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum. Ketiganya saling berkaitan dan harus bergerak simultan agar penegakan hukum berjalan efektif. Cacat pada salah satu komponen akan menggagalkan atau mengurangi kualitas efektifitas penegakan hukum.
Subtansi hukum dimengerti sebagai kaidah atau norma hukum. Lebih sempit, ia sering diartikan sebagai peraturan perundang-undangan. Menurut Satjipto Rahardjo (2009:24), penegakan hukum dimulai pada saat peraturan hukum itu dibuat. Maka, ketika badan pembuat undang-undang membuat peraturan yang sulit dilaksanakan dalam masyarakat, maka sejak itu sebenarnya terjadi persoalan penegakan hukum. Peraturan yang dibentuk sangat menentukan proses penegakan hukum ketika berlaku.
Subtansi hukum yang berisi ide-ide abstrak tersebut tidak akan menjadi nyata apabila hanya dibiarkan sebatas tersusun di lembaran naskah serta diumumkan keberlakuannya. Untuk itu, struktur hukum diperlukan guna melengkapi subtansi hukum. Maka, negara sebagai penyelenggara hukum membentuk suatu badan atau organisasi yang bertugas menerapkan hukum, seperti, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lain-lain.
Adapun budaya hukum adalah keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempatnya yang logis dalam kerangka budaya milik masyarakat. Budaya hukum juga sering diartikan sebagai kesadaran masyarakat. Maka, budaya hukum juga dipahami sebagai kerelaan warga negara untuk tunduk pada hukum. Upaya membangun kesadaran masyarakat ini penting untuk penegakan hukum, karena hukum dibuat untuk mengatur masyarakat.
Membangun Budaya Hukum
Selama ini, banyak yang terjebak pada pemahaman bahwa penegakan hukum hanya seputar subtansi dan struktur hukum. Lebih sempit lagi, hanya dimengerti sebagai pidana dan sanksi. Penegakan hukum hanya diartikan sebagai reaksi terhadap pelanggaran. Ketika suatu aturan dilanggar, di situlah hukum harus ditegakkan. Pemahaman sempit inilah yang mengasingkan hukum sehingga hukum tak mampu menjawab persoalan sosial.
Padahal sesungguhnya, lebih luas, penegakan hukum harus dipahami dalam arti preventif. Ketika sebuah peraturan hukum disahkan dan berlaku, harus segera diimplementasikan. Peraturan tersebut harus segera dibumikan dalam kehidupan masyarakat. Dan itu harus menjadi gerakan sosial-kolektif. Karena tujuan hukum sendiri untuk mengatur masyarakat. Masyarakat harus diberi pengertian, dibangun kesadaran dan kepatuhannya, serta diajak bersama mewujudkan cita-cita hukum yang diusung oleh sebuah peraturan.
Hukum harus menemukan konteks sosialnya. Karena itu, budaya hukum harus diperhatikan. Dalam konteks UU Desa, partisipasi masyarakat harus dibangun. Pemerintah sebagai pemangku kebijakan harus mampu mengupayakan itu. Hal itu juga bagian dari penegakan hukum. Penegakan hukum yang memperhatikan budaya hukum dan kesadaran masyarakat, justru akan lebih efektif untuk mewujudkan ide-ide abstrak subtansi hukum itu sendiri. Hukum harus sedini mungkin menjadi gerakan sosial untuk mewujudkan tujuan bersama.
Untuk itu, masyarakat perlu dibekali beberapa hal tentang UU Desa. Hal itu akan menjadi modal bagi masyarakat untuk berpartisipasi. Bukan saja untuk mengawasi, modal pengetahuan itu juga akan menyadarkan masyarakat akan hak-haknya sehingga pembangunan partisipatif terwujud. Bukankah itu yang diimpikan UU Desa? Yakni keterlibatan warga dalam perencanaan sampai eksekusi pembangunan. Kegotongroyongan sebagai nilai dan praktik yang hidup di desa, menjadi salah satu prinsip dalam UU Desa,.
Itulah yang disebut penegakan hukum dalam arti preventif-sosiologis. Mewujudkan ide-ide abtrak subtansi hukum dimulai sejak awal dengan mengkombinasikan terbangunnya tiga pilar penegakan hukum dengan baik, yaitu, subtansi, struktur dan kultur hukum. Kesadaran masyarakar harus dibangun, agar partisipasi masyarakat terwujud. Dengan begitu, dengan sendirinya telah terbangun pengawasan sosial. Hal itu jauh lebih menguntungkan daripada tereduksi pada pendekatan represif semata.
Dengan begitu, pembangunan, dari perencanaan sampai pelaksanaan, berjalan dengan baik karena memperhatikan prinsip-prinsip yang diatur oleh undang-undang. Hukum diimplementasikan sebagai sebuah gerakan sosial untuk mewujudkan cita-cita kehidupan bersama. Bila sudah demikian, rasanya sangat kecil peluang terjadinya korupsi atau penyelewengan dalam praktik pemerintahan desa. Masing-masing pihak memainkan perannya dengan baik, yakni pemerintah dan masyarakat.
Sebaliknya, ketika hukum hanya dimaknai secara represif, seringkali kultur hukum terabaikan. Hukum sekedar diartikan secara formal-legalistik, dan tak dibumikan dengan baik di masyarakat. Hukum hanya dimengerti sebagai kaidah yang beroperasi ketika terjadi pelanggaran. Di masyarakat desa yang kolektif dan masih kuat tradisi kekerabatannya, pendekatan hukum represif justru berpotensi memupuk resiko konflik yang besar. Ini yang perlu diperhatikan.
Penulis bukan menolak pelibatan polisi dalam pengawasan dana desa. Sebaliknya, penulis justru mendukungnya. Namun upaya itu, jangan sampai justru merusak budaya hukum di masyarakat desa. Masyarakat desa berbeda dengan masyarakat kota. Upaya-upaya litigatif masih terbilang tabu. Karena itu, pendekatan pidana harus benar-benar sebagai ultimum remidium atau upaya terakhir. Sebelum itu, gerakan sosial melalui budaya hukum harus terbangun dulu. Hukum harus dibumikan di masyarakat sehingga tidak mengalami keterasingan.
Terbangunnya peran masyarakat tersebut, juga dapat diinisiasi oleh masyarakat sendiri. Dalam hal ini, peran organisasi masyarakat seperti NU sangat strategis. Sebagai ormas terbesar, juga memiliki basis massa di desa yang besar, NU bertanggung secara sosiologis untuk turut membangun partisipasi masyarakat tersebut. Terlebih, NU juga berkepentingan untuk mengatasi persoalan kemiskinan dan ketertinggalan di desa. Prioritas pembangunan desa oleh pemerintah harus dimanfaatkan NU dengan baik.
*
Penulis adalah pelajar NU di Gresik, Jawa Timur.