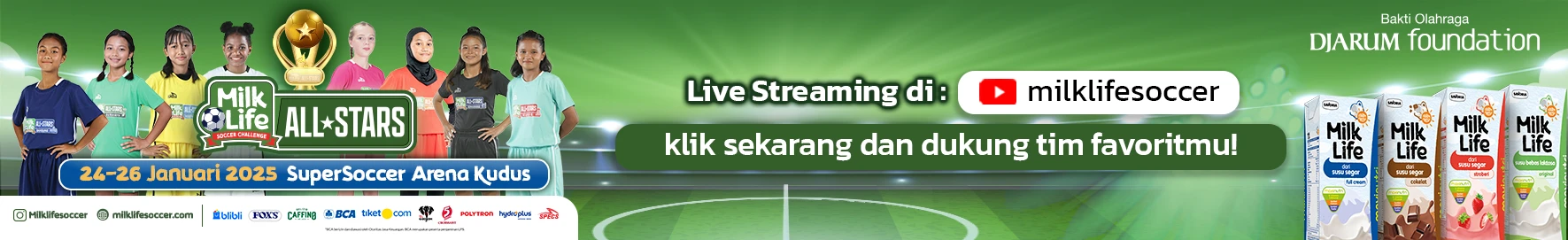Oleh Muhammad Afiq Zahara
Mahatma Ghandi mengatakan: “Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever—hiduplah seperti kau akan mati besok. Belajarlah seperti kau akan hidup selamanya.”
Menurut saya, salah satu kebahagiaan terbesar manusia adalah anugerah Tuhan berupa kemampuan belajar. Manusia diberikan kapabilitas mempelajari kesalahannya, memahami hal baru dan mengobservasi segala sesuatu. Tidak semua makhluk Tuhan memiliki kemewahan itu. Manusia dapat melakukan penalaran dan ekstraksi terhadap apa saja yang ada di sekitarnya. Kapasitas ingatannya pun luar biasa. Inilah yang membuat manusia sebagai makhluk tercerdas yang diciptakan Allah. Tapi, apakah manusia telah benar-benar memanfaatkan kemewahan itu dengan benar? Itu persoalan lain.
Saya tidak akan masuk pada pembahasan tentang bagaimana menyusun kurikulum pesantren yang baik. Tulisan ini tidak mengkaji tentang itu. Tulisan ini lebih kepada konstruksi kemandirian belajar santri sebagai pribadi. Sebab, tidak bisa dipungkiri, kemandirian belajar selalu menjadi masalah dalam sistem atau skema belajar-mengajar. Tidak hanya di pesantren, tapi institusi pendidikan lainnya juga. Ketika kegiatan kelas atau pengajian resmi di pesantren telah usai, banyak murid dan santri yang tidak membangun kemandirian belajarnya.
Saya hampir yakin, keberhasilan dalam belajar lebih dari 65 persen karena kemandiriannya, sisanya karena sistem dan kurikulum yang baik. Bayangkan jika kurikulumnya kurang mendukung, tanpa kemandirian belajar, keberhasilan dalam menyerap pengetahuan akan semakin sukar. Dari perspektif ini, kemandirian belajar (self-education) yang dilengkapi dengan sistem pendidikan yang baik merupakan bentuk ideal dalam pengembangan intelektual para santri.
Potensi pondok pesantren lebih besar dari institusi pendidikan lainnnya. Kultur belajar di pesantren, dengan beragam pendekatannya, seperti sorogan, setoran dan bandongan, mengharuskan santri untuk mempersiapkan pelajarannya terlebih dahulu sebelum masuk jam pelajaran. Di samping lingkungannya yang mendukung (diasramakan). Permasalahannya terletak pada kemandirian belajar santri sekadar pengguguran kewajiban, bukan karena dorongan pribadi. Sehingga banyak santri yang hafal Alfiyyah, al-Jurumiyyah dan kitab-kitab wajib pesantren tanpa memahami kandungan dan cara penggunaannya. Ini adalah masalah yang harus cepat dibenahi.
Untuk mengurainya, kita harus melihat ke belakang, meninjau dan memperhatikan kemandirian belajar para ulama di masa lalu sebagai intsrumen keteladanan. Dengan berbagai keterbatasan sarana, para ulama masa lalu mampu mencetakkan dirinya sebagai putra sejarah, mewarnai gelanggang intelektual dan arena ilmu pengetahuan. Karya-karyanya dibaca hampir di seluruh penjuru dunia. Jerih payahnya diwariskan dari generasi ke generasi. Bisa jadi inilah yang dimaksud dengan umur panjang yang sesungguhnya, meski telah ratusan bahkan ribuan tahun meninggal, mereka tetap hidup melalui peninggalannya, dan mempengaruhi kita dengan hasil belajarnya. Dari mereka kita bisa mempelajari beberapa hal.
Pertama, mengulang pelajarannya berkali-kali, tidak sekadar untuk melestarikan hafalannya, tapi mencari faidah baru yang terlewati sebelumnya. Misalnya Imam al-Muzani (791-877 M), murid Imam Syafi’i. Ia pernah mengatakan: “qara’tu kitâb al-risâlah li al-syâfi’i khams mi’ah marrah, mâ min marrah minhâ illâ wa istafadtu fâidatan jadîdatan lam astafiduhâ fi al-ukhra—aku telah membaca kitab al-Risalah Imam Syafi’i lima ratus kali, setiap kali membacanya aku menemukan faidah baru yang tidak kutemukan sebelumnya.” (Yahya bin Syarraf al-Nawawi, al-Majmû’ Syarh al-Muhadzdzab, juz 1, hlm 26).
Dalam membaca pelajaran atau sebuah buku, diantara yang kita pahami dengan baik, masih banyak bagian yang tidak kita pahami dan terlewat begitu saja. Tanpa melakukan pengulangan, bagian-bagian yang terlewati atau yang belum terpahami itu tidak akan tersentuh. Akibatnya, kita tidak mampu memahami seluruh pelajaran atau isi buku itu dengan baik.
Kedua, berusaha memahami terlebih dahulu pelajaran yang hendak didapatkan, seperti Imam al-Syafi’i.Sebelum menjadi murid Imam Malik, Ia telah mempelajari dan menghafal seluruh isi kitab al-Muwatha. Tujuannya adalah, agar Ia dapat mengikuti pelajaran yang diberikan Imam Malik dengan baik. Hal ini penting. Sebab, banyak siswa yang terjebak dalam lingkaran ketidak-pahaman ketika menerima pelajaran di kelas. Sehingga proses transfer of knowledge tidak berjalan lancar.Karena sedikit pun mereka tidak memahami apa yang hendak diajarkan. Akan berbeda jika mereka mempersiapkan diri terlebih dahulu sebelum menerima pelajaran.
Ketiga, kreatif dalam menghafal dan mengulang pelajaran. Kreatifitas dalam belajar sangat penting untuk mengembangkan kemandirian belajar santri. Pendekatannya bisa beragam. Contoh menarik pernah ditunjukkan oleh Imam Ikliya al-Harawi (1058-1110 M), murid Imam al-Haramain al-Juwaini dan teman Imam al-Ghazali. Ia mengatakan:
كانت في مدرسة سرهنك بنيسابور قناة لها سبعون درجة وكنت إذا حفظت الدرس أنزل القناة وأعيد الدرس في كل درجة مرة في الصعود والنزول قال وكذا كنت أفعل في كل درس حفظته
“Di Madrasah Sarhank di Naisabur terdapat sungai yang memiliki 70 anak tangga. Ketika aku menghafal pelajaran, aku turun ke sungai sembari mengulang hafalan pelajaranku satu kali di setiap anak tangga. Aku melakukannya di saat naik dan turun. Begitulah yang kulakukan setiap kali menghafal sebuah pelajaran.” (al-Subki, Thabaqat Syafi’iyyah al-Kubra, juz 7, hlm 233).
Kreativitas semacam itu harus dimiliki para santri, agar mereka dapat mengembangkan potensinya lebih jauh. Kita sering mendengar bahwa menjadi santri harus “prihatin”. Menurut saya, “prihatin” dalam konteks yang lebih luas bukan hanya nrimo (tirakat) kesusahan makan, minum dan tiadanya hiburan, tapi juga kemandirian belajar. Apa yang ditunjukkan oleh Imam al-Muzani, Imam al-Syafi’i dan Imam Ikliya al-Harawi merupakan bentuk keprihatinan yang lengkap, yaitu sabar dalam menghafal pelajaran sekaligus sabar dalam menjalani kehidupan santri yang serba terbatas dan susah.
Oleh karena itu, para santri harus mulai membenih kemandirian belajarnya, serta menjadikannya sebagai gaya hidup. Belajar sendiri (self-education) adalah pembeda bagi kemajuan santri. Kiai-kiai kita di masa lalu menghabiskan banyak waktu dalam kemandirian ini. Mereka belajar di dalam maupun di luar kelas. Kita pun tidak bisa menutup mata, banyak juga teman-teman kiai kita yang tidak meninggalkan karya seperti mereka. Barangkali—atau hampir pasti—jumlah mereka lebih banyak dari kiai-kiai yang kita kenal itu. Intelektualitas memang bukan segalanya, tapi segala kemajuan di dunia terkait dengan intelektualitas manusia. Wallahu a’lam.
Penulis adalah alumnus Pondok Pesamtren al-Islah, Kaliketing, Doro, Pekalongan dan Pondok Pesantren Darussa’adah, Bulus, Kritig, Petanahan, Kebumen.