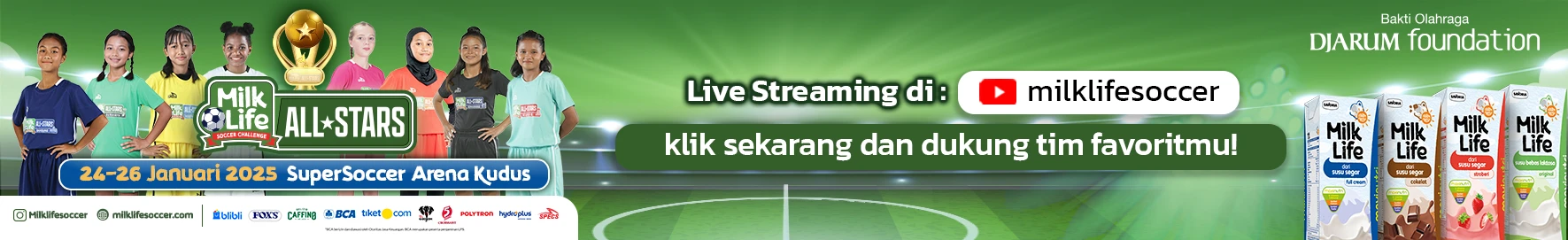Oleh: Achmad Faiz MN Abdalla
Dalam sebuah perkuliahan, sang dosen menjelaskan beberapa teori berlakunya hukum Islam di Indonesia. Teori-teori tersebut disampaikan sebagai bagian dari materi mata kuliah Peradilan Agama.
Secara sosiologis, peradilan agama telah ada di Indonesia seiring berkembangnya Islam di nusantara. Peradilan agama pun pada perkembangannya ditingkatkan menjadi pengadilan negara. Sampai sekarang. Karena itu, peradilan agama menjadi salah satu mata kuliah penting di fakultas hukum dan syariah di Indonesia.
Sang dosen memulainya dengan menjelaskan sejarah peradilan agama di Indonesia. Disampaikannya, peradilan agama sudah dikenal sebelum berdirinya kerajaan-kerajaan Islam. Seiring berkuasanya kerajaan-kerajaan Islam, peradilan agama mendapatkan kedudukan yang sempurna dalam sistem ketatanegaraan kerajaan-kerajaan Islam.
Masing-masing daerah pun memiliki penyebutan yang beragam, seperti pengadilan serambi, kerapatan qadhi,
pengadilan penghulu dan lainnya. Hal itu menunjukkan bahwa peradilan agama memiliki akar historis-sosiologis di berbagai belahan nusantara.
Pada masa itu, semua perkara menjadi kompetensi peradilan agama. Baik perkara perdata maupun publik. Keadaan tersebut berubah seiring berkuasanya Belanda di Indonesia. Dimulai kedatangan VOC pada tahun 1602. Belanda menjajah Indonesia dengan membawa segala pengaruhnya, termasuk di bidang hukum dan peradilan.
Mula-mula sikap politik Belanda terhadap peradilan agama adalah princepeel gebrekkig mar fietelijk onmisbar. Yakni, peradilan agama tidak diperlukan tetapi kenyataannya harus ada. Belanda tidak memerlukan hukum Islam dan peradilan agama. Tetapi karena diperlukan rakyat jajahan, maka harus diadakan agar tidak mendapat perlawanan.
Politik hukum itu didasarkan pada teori receptio in complexu yang berintikan bahwa hukum mengikuti agama yang dianut seseorang. Jika memeluk Islam, maka hukum Islam yang berlaku baginya. Karena itu, hukum yang berlaku di Jawa adalah hukum Islam. Teori ini dipelopori van Den Berg dan diterapkan ke dalam sistem ketatanegaraan melalui peraturan perundang-undangan Hindia Belanda.
Selanjutnya, teori itu menjadi dasar dilahirkannya Stbl 1882 No. 152 yang mengangkat peradilan agama menjadi pengadilan negara Pemerintah Hindia Belanda (Mukti Arto, 2012: 88). Meski diakui, kompetensi peradilan agama bersifat terbatas.
Dalam perkembangannya, politik hukum Hindia Belanda mengalami perubahan. Snouck Hurgronje menentang teori receptio in complexu dengan mengemukakan teori baru, yaitu teori receptie yang menyatakan, hukum yang berlaku di Indonesia sesungguhnya bukan hukum Islam, melainkan hukum adat. Hukum Islam dapat berlaku sepanjang tidak bertentangan dan sudah diresepsi menjadi hukum adat.
Teori receptie kemudian diterapkan melalui penggantian UU Dasar Hindia Belanda, yaitu dari Regeringsreglement (RR) menjadi Indischestaatsregeling (IS). Perubahan tersebut terjadi karena perubahan politik hukum yang sangat mendasar, bahwa teori receptio in complexu ternyata tidak menguntungkan kepentingan politik Pemerintah Belanda.
Diterangkan sang dosen, teori receptie tersebut masih mempengaruhi perkembangan hukum dan peradilan di Indonesia setelah merdeka. Menurutnya, seharusnya pengaturan hukum dan peradilan setelah merdeka dibersihkan dari teori receptie, mengingat teori tersebut merupakan bagian dari politik hukum kolonial.
Dengan begitu, peradilan agama memiliki peran yang lebih kuat dalam dunia peradilan di Indonesia. Selama dijajah Belanda, terutama sejak berlakunya teori receptie, peran peradilan agama serta hukum Islam sengaja direduksi.
Di tengah penjelasan sang dosen itu, salah seorang mahasiswa mengajukan pertanyaan, “Pak, bila pengakuan negara terhadap peradilan agama sangat erat kaitannya dengan sejarah panjang peradilan agama di nusantara, apakah hal itu membenarkan Islam Nusantara?”
Menjawab pertanyaan itu, sang dosen membenarkan bahwa keberadaan peradilan agama dalam hukum positif didasarkan pada praktik peradilan agama yang hidup berabad-abad di tengah masyarakat nusantara. Namun ia tidak sependapat dengan gagasan Islam Nusantara.
Menurutnya, Islam Nusantara justru memiliki semangat yang sama dengan teori receptie yang membatasi Islam dengan budaya. Ia melanjutkan, Islam bukanlah agama yang anti budaya. Namun, antara agama dan budaya haruslah dipisahkan, tidak dicampur, apalagi budaya sampai mereduksi atau meresepsi ajaran Islam.
Jawaban tersebut, menurut penulis, menunjukkan kekurangmengertian sang dosen terhadap gagasan Islam Nusantara. Dari jawaban itu, dapat disimpulkan, bahwa seperti halnya teori receptie, Islam Nusantara adalah budaya yang meresepsi ajaran Islam. Artinya, ajaran Islam berlaku bukan sebagai wajah Islam sendiri, tapi ia lebih dulu harus diresepsi oleh budaya.
Itu jelas pemahaman yang keliru tentang Islam Nusantara.
Islam Nusantara sendiri, menurut Oman Fathurrohman (2015), bukanlah Islam yang normatif, tapi Islam empirik sebagai hasil interaksi, kontekstualisasi, indigenisasi, penerjemahan, vernakularisasi Islam universal dengan realitas sosial dan budaya di Indonesia.
Sedangkan menurut Kiai Afifudin Muhajir (2015), Islam Nusantara adalah paham dan praktik keislaman di bumi Nusantara sebagai hasil dialektika antara teks syariat dengan realita dan budaya setempat.
Pengertian terakhir bernuasan fiqih. Namun dapat disimpulkan, kedua pengertian di atas memiliki inti yang sama, yakni interaksi dan dialektika antara unsur normatif dan empiris.
Lebih khusus lagi, Kiai Afifudin juga menyebut istilah Fiqih Nusantara. Ia adalah paham dan perspektif keislaman di bumi Nusantara sebagai hasil dialektika teks-teks syariat dan budaya, juga realitas di (daerah) setempat.
Dijelaskan oleh Kiai Afifudin, bahwa Islam bukanlah budaya karena yang pertama bersifat ilahiyah sementara yang kedua adalah insaniyah. Akan tetapi, berhubung Islam juga dipraktikkan oleh manusia, maka pada satu dimensi ia bersifat insaniyah dan karenanya tidak mengancam eksistensi kebudayaan.
Karena itu, selain memiliki landasan nash-nash syariat (Al-Quran dan Sunah), Islam juga memiliki acuan maqasidus syariah (tujuan syariat). Nash-nash syariat yang dipahami dengan memperhatikan maqasidus syariʻah akan melahirkan hukum yang tidak selalu tekstual, tetapi juga kontekstual.
Maka, menurut Kiai Afifudin, penting adanya pemahaman kontekstual terhadap teks suci dengan mempertimbangkan adat lokal (urf) demi kemaslahatan. Dari sinilah, meminjam istilah Kiai Said Aqil Siradj, Islam Nusantara adalah perspektif yang membangun Islam di atas infrastruktur budaya.
Dari penjelasan itu, sekali lagi, dapat ditarik pola hubungan Islam dan Nusantara dalam gagasan Islam Nusantara, yakni interaksi dan dialektika unsur normatif dan empiris yang bersifat konstruktif dan komplementer.
Itu tentu berbeda dengan pengertian teori receptie. Teori itu dibangun dari persepsi, bahwa Islam dan adat adalah dua unsur yang saling bertentangan. Itu dapat dipahami, karena Belanda membangun teori konflik dalam melihat hubungan dua sistem berbeda tersebut.
Maka, sikap Belanda terhadap kedua sistem itu dapat diumpamakan seperti sikap orang membelah bambu, mengangkat belahan yang satu dan menekan belahan yang lain (Mohammad Daud Ali, 2014:224). Dalam teori receptie, adat yang diangkat, sedangkan Islam yang ditekan.
Nah, yang perlu dicatat, praktik hubungan Islam dengan adat nusantara sejak semula sesungguhnya sangat akrab. Misal, di dalam masyarakat Minangkabau, tercermin dari pepatah: adat dan syara sanda menyanda, syara’ mengato adat memakai.
Menurut Hamka (1970), makna pepatah itu adalah hubungan adat dengan hukum Islam (syara) erat sekali, saling topang-menopang, karena sesungguhnya yang dinamakan adat benar-benar adat adalah syara itu sendiri. Praktik semacam itu tidak hanya di Minangkabau, tapi hampir menyeluruh di belahan nusantara.
Maka menurut Sajuti Thalib (1980), sesungguhnya yang berlaku adalah teori receptio a contrario, yakni hukum adat baru berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam. Yang dipergunakan tentu bukan sembarang adat, melainkan terbatas pada yang serasi dengan asas-asas hukum Islam.
Sebaliknya, teori receptie dibangun tidak lebih hanya ambisi Belanda untuk menjauhkan pengaruh hukum Islam dari pemeluknya demi kepentingan kolonialnya.
Oleh karena itu, dalam melihat hubungan Islam dan adat, khususnya dalam konteks hukum, menurut Hasbi Ash-Shiddieqy (1975), di dalam kitab-kitab fiqih Islam banyak sekali garis-garis hukum yang dibina atas dasar urf atau adat karena para ahli hukum telah menjadikan urf sebagai salah satu sarana untuk pembentukan hukum Islam.
Dapat disimpulkan, sesungguhnya Islam Nusantara adalah penegasan dari praktik yang telah hidup berabad-abad. Islam Nusantara bukanlah hal yang baru. Ia ada seiring berkembangnya Islam di nusantara. Yang selanjutnya oleh NU, digali, dirumuskan dan dikembangkan lagi, untuk menjawab tantangan Islam dan kebangsaan di masa yang akan datang.
(Penulis adalah pelajar NU di Gresik, Jawa Timur)
Baca tulisan opini lainnya DI SINI
Terkait
Terpopuler
1
Kemenag Tetapkan Gelar Akademik Baru untuk Lulusan Ma’had Aly
2
LKKNU Jakarta Perkuat Kesehatan Mental Keluarga
3
Anggapan Safar sebagai Bulan Sial Berseberangan dengan Pandangan Ulama
4
3 Alasan Bulan Kedua Hijriah Dinamakan Safar
5
Kopri PB PMII Luncurkan Beasiswa Pendidikan Khusus Profesi Advokat untuk 2.000 Kader Perempuan
6
Abi Mudi Samalanga Dianugerahi Penghargaan Kategori Ulama Berpengaruh di Aceh
Terkini
Lihat Semua